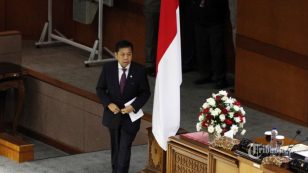Kabar Berita.id –Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) adalah sebuah institusi. tapi di tangan Setya Novanto, lembaga ini bisa dipersonalisasi (dibuat menjadi bersifat personal), tak lagi institusional.
Betapa tidak? Saat dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi perkara korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, Senin (6/11/2017), Ketua DPR itu tidak hadir dengan “menyandera” Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPR Damayanti melalui perintah melayangkan selembar surat.
Surat pun kemudian dibuat.
Melalui surat tertanggal 6 November 2017 yang ditandatangani Damayanti beberapa menit sebelum dikirim ke KPK, Novanto berdalih untuk memeriksa dirinya KPK harus seizin Presiden atau Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 yang menyatakan setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu; dan juga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD.
Damayanti mengklaim, perintah menerbitkan surat yang dilayangkan Novanto melalui Ketua Badan Keahlian DPR Johnson Rajagukguk adalah teknis biasa dalam proses administrasi.
Ia meyakini tim Biro Pimpinan DPR sudah memiliki kajian hukum dalam membuat surat tersebut. Ia membantah jika keputusannya itu dianggap turut menghalangi proses penegakan hukum di KPK.
Memang, Sekretariat Jenderal DPR merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga. Dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2015 tentang Setjen dan Badan Keahlian DPR dinyatakan bahwa Setjen dan BK adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR.
Dari titik ini Damayanti selanjutnya bisa lepas tangan, meski masih patut dipertanyakan, apakah permintaan Novanto itu bersifat kelembagaan, bukan personal, mengingat kedudukan Setjen sebagai kesekretariatan lembaga, bukan sekretaris pribadi Novanto?
Damayanti bertambah “merdeka” ketika Fredrich Yunadi, kuasa hukum Novanto, mengatakan, pengiriman surat pemberitahuan ketidakhadiran yang berlogokan DPR ke KPK atas inisiatif kliennya (Kompas.com, 7 November 2017).
Bukan kali ini saja Novanto yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu mempersonalisasi institusi DPR. Pada 22 September 2017, saat hendak diperiksa KPK sebagai tersangka korupsi e-KTP, DPR juga berkirim surat ke KPK.
Surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon itu berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Setya Novanto karena Ketua DPR itu sedang mengajukan gugatan praperadilan. Pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum.
Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung. Pada 29 Oktober 2017, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar mengabulkan praperadilan Novanto. Status tersangka yang disandang Novanto sejak 17 Juli 2017 pun gugur.
Sesungguhnya apa pun status Novanto, sebagai saksi atau pun tersangka korupsi, tidak terkait dengan jabatannya sebagai Ketua DPR. Status itu merupakan dampak dari perbuatan personal/individual, bukan institusi DPR, meskipun saat kasus itu terjadi, 2011-2012, posisi Novanto sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.
Pasal 86 UU MD3 menyebutkan, tugas Pimpinan DPR antara lain memimpin dan menyimpulkan hasil sidang, menyusun rencana kerja, melakukan koordinasi, dan menjadi juru bicara DPR.
Novanto adalah anggota DPR, dan sebagai anggota DPR, ia berkedudukan sama dengan 559 anggota DPR lainnya, tak kurang dan tak lebih.
Bahwa jabatannya sebagai Ketua DPR, itu hanya sebatas juru bicara yang mewakili institusi DPR. Setya Novanto bukan DPR, dan DPR bukan Setya Novanto.
Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, Novanto melakukan blunder. Sebab, pada Pasal 245 ayat (3) huruf c UU MD3 disebutkan bahwa ketentuan pada ayat (1) tidak berlaku terhadap anggota DPR yang disangka melakukan tindak pidana khusus. Korupsi adalah tindak pidana khusus bahkan dilabeli sebagai extraordinary crime.
Jadi tidak ada alasan bagi Novanto untuk mangkir dari pemeriksaan KPK. Novanto kurang cermat karena hanya melihat satu ayat pada pasal tersebut (Kompas.com, 6 November 2017).
Mantan hakim MK Harjono juga berpendapat, MK saat itu tidak mengubah Pasal 245 ayat (3) yang menyatakan ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR diduga melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi. Oleh karena itu, KPK tetap berwenang memeriksa Novanto meski tanpa izin Presiden.
Di pihak lain, KPK bekerja berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 yang bersifat lex specialis. Dalam hukum dikenal lex specialis derogate legi generalis, aturan khusus menyimpangi aturan umum.Itulah sebabnya, meski Pimpinan DPR bersurat ke KPK agar menunda penyidikan terhadap Novanto, KPK tak mengindahkannya.
Sumber : Tribunnews.com